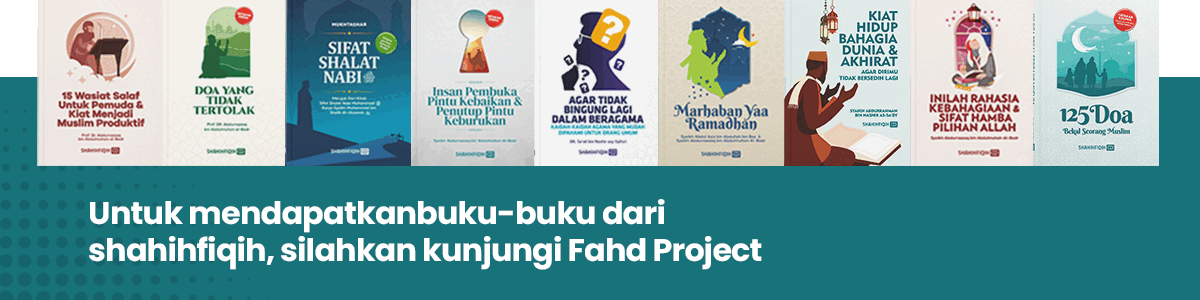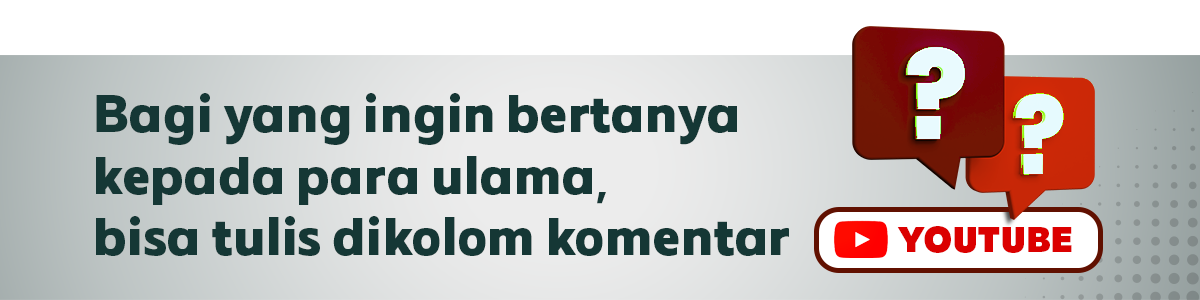Secara umum, zakat barang dagangan memiliki aturan yang mirip dengan zakat emas dan perak. Yaitu, nilai barang dagangan tersebut harus mencapai batas minimal nishab yang setara 85 gr emas, dan bertahan selama satu tahun hijriah (haul). Jika syarat ini terpenuhi, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari total nilainya. (Lihat: Al-Muhith Al-Burhani 2/246)
Perlu diketahui juga bahwa nilai barang dagangan digabungkan dengan emas atau perak (termasuk juga uang kartal), untuk menyempurnakan nishab. Dengan kata lain, jika seseorang memiliki barang dagangan dan juga emas, perak, atau uang tunai, maka nilainya bisa digabungkan untuk mencapai nishab.
Al-Khattabi berkata: “Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mayoritas (ulama) bahwa seseorang yang memiliki seratus dirham dan juga memiliki barang dagangan senilai seratus dirham, lalu keduanya telah mencapai haul (satu tahun), maka salah satu digabungkan dengan yang lain, dan zakat wajib atas keduanya.” (Lihat: Ma’alim As-Sunan 2/16)
Dan masih ada perincian tentang masalah lain terkait, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam artikel ini.
Di antara dalil yang menunjukkan kewajiban zakat barang dagangan adalah firman Allah Ta’ala:
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ
“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.” (QS. Al-Baqarah: 267)
Imam Mujahid menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah perintah untuk berinfak dari hasil barang dagangan. (Lihat: Tafsir Ibnu Katsir 1/697)
Diriwayatkan bahwa Umar pernah melewati Himas bin Amr, lalu ia berkata, “Wahai Himas, bayarkan zakat hartamu!” Himas menjawab, “Aku tidak memiliki harta kecuali kantong-kantong dan kulit.” Maka Umar berkata,
قَوِّمْهَا قِيمَةً ثُمَّ أَدِّ زَكَاتَهَا
“Taksirlah nilainya, lalu bayarkan zakatnya!” (HR. Abu Ubaid, no. 1179)
Kapan perhitungan haul dimulai?
Perhitungan haul dimulai sejak seseorang berniat berdagang dengan barang yang sudah ia miliki sebagai modal awal. Syaratnya, nilai modal tersebut sudah mencapai nishab, dan bertahan satu haul. Jika nilai barang dagangan (modal) saat pertama kali dimiliki masih kurang dari nishab, maka perhitungan haul belum dimulai sampai nilainya mencapai nishab. (Lihat: Al-Mughni 3/23, Asy-Syarh Al-Mumti’ 6/143)
Dalam salah satu riwayat dari madzhab Imam Ahmad disebutkan: Bahwa syarat barang dagangan dikenakan zakat, seseorang tidak harus mendapatkan modal awalnya dengan perbuatannya sendiri, seperti upah pekerjaannya, atau pemberian dari orang, dan juga tidak harus modal itu berasal dari transaksi. Barang apa pun, meskipun dari warisan, jika sudah diniatkan untuk menjadi modal awal bisnis, maka dianggap sebagai barang dagangan yang wajib dizakati. (Lihat: Al-Mughni 3/31)
Dalilnya adalah keumuman sabda Nabi ﷺ dalam hadits Samurah bin Jundub:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِمَّا نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ
“Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari apa yang kami siapkan untuk dijual.” (HR. Abu Dawud, no. 1562)
Dan hukum asal barang-barang adalah untuk kepemilikan pribadi (bukan dagangan), maka perlu niat berdagang untuk memalingkan dari hukum asalnya. (Lihat: Fathul Qadir 2/218, Kasyaf Al-Qina’ 2/240)
Jika seseorang memiliki barang dengan niat untuk dimiliki pribadi (bukan untuk dagang), lalu kemudian ia berniat menjualnya, maka dihitung sebagai barang dagangan. Sebaliknya, jika awalnya diniatkan untuk dagang, lalu berubah niat untuk kepemilikan pribadi, maka ia tidak lagi dianggap sebagai barang dagangan dan tidak wajib dizakati. (Lihat: Al-Bahr Ar-Raiq 226, At-Taj wal Iklil 2/303, Al-Majmu’ 6/48, Kasyaf Al-Qina 2/240)
Mazhab Hanafiyah mengecualikan satu hal, yaitu barang yang dibeli oleh mudharib (pengelola dana dalam akad mudharabah). Dalam hal ini, barang itu otomatis dianggap sebagai barang dagangan, karena mudharib tidak boleh menggunakan harta mudharabah kecuali untuk berdagang. (Lihat: Hasyiyah Ibni Abidin 2/268)
Bagaimana dengan niat menyewakan barang dan menjualnya sekaligus?
Dalam madzhab Maliki: Jika seseorang meniatkan dua hal sekaligus saat membeli barang, yaitu untuk disewakan terlebih dahulu, dan jika untung akan dijual, maka menurut pendapat yang lebih kuat, tetap wajib zakat atas barang itu. Begitu juga jika ia berniat memanfaatkan barang itu dulu seperti menunggangi hewan atau tinggal di rumahnya, lalu jika ada peluang untung ia akan menjualnya, maka tetap dikenakan zakat. (Lihat: At-Taj wal Iklil 3/182)
Namun, jika seseorang memiliki barang itu hanya untuk dimiliki pribadi saja, atau hanya untuk disewakan, atau untuk pribadi dan disewakan, atau tanpa niat apa pun, maka tidak wajib zakat atasnya.
Apa saja barang yang terkena zakat?
Batasan inti dalam zakat barang dagangan adalah segala sesuatu yang dimiliki dengan niat untuk diperjualbelikan, baik dalam bentuk barang jadi maupun bahan pelengkap yang melekat pada produk yang dijual. (Lihat: Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah 23/274)
Contoh barang yang diniatkan untuk dijual (yang dihitung zakatnya):
• Barang dagangan di gudang, toko, dalam perjalanan, atau dititipkan ke distributor.
• Barang di pabrik (baik yang siap jual maupun masih dalam proses produksi).
• Barang yang dibeli dengan sistem salam, istishna‘, atau sesuai spesifikasi.
• Perhiasan yang diniatkan untuk dijual.
• Saham yang dibeli dengan niat untuk diperjualbelikan.
• Tanah atau properti yang dibeli dengan niat untuk diperjualbelikan.
• Manfaat (seperti lisensi, hak cipta) jika dibeli dengan niat untuk diperjualbelikan.
• Bahan pembungkus/kemasan jika diserahkan bersama barang ke pembeli.
• Bahan produksi yang tersisa dalam barang jadi (contoh: gula, susu dalam pembuatan kue).
• Bahan pewarna, penyamak kulit, minyak pelumas jika efeknya masih ada pada produk akhir.
Adapun yang tidak dihitung zakatnya adalah harta yang tidak diniatkan untuk dijual, seperti:
• Aset tetap (bangunan, kendaraan operasional, peralatan produksi).
• Modal, cadangan, dan keuntungan usaha yang belum diwujudkan kembali dalam barang dagangan.
• Kekayaan tidak berwujud (seperti nama usaha, merek dagang), kecuali jika dibeli untuk dijual.
• Barang penunjang usaha yang tidak dijual: etalase, rak, lemari, botol parfum (yang tidak dijual).
• Bahan pembungkus yang hanya untuk penyimpanan di toko (tidak ikut diberikan ke pembeli).
• Alat produksi (mesin jahit, oven, alat cetak, dll.).
• Kendaraan operasional perusahaan.
• Bangunan/peralatan yang digunakan untuk usaha (bukan untuk dijual).
• Bahan habis pakai: sabun, bahan pembersih, bahan bakar, dll.
• Pakan hewan usaha.
• Peralatan pendukung produksi (panci, alat aduk, dll.).
Rumus Menghitung Zakat Barang Dagangan
Jumlah zakat = uang tunai yang ingin diputar kembali + nilai seluruh barang dagangan pada saat haul (yang ada di toko maupun gudang) – utang yang dimiliki × 2,5%
Dasar rumus ini berasal dari beberapa riwayat salaf, di antaranya yang datang dari Maimun bin Mihran rahimahullah, bahwa ia berkata:
إِذَا حَلَّتْ عَلَيْكَ الزَّكَاةَ؛ فَانْظُرْ كُلَّ مَالٍ لَكَ، ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ الدَّيْنِ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ
“Apabila zakat (barang dagangan) telah jatuh tempo atasmu, maka lihatlah semua hartamu, lalu kurangkan darinya utang-utangmu, kemudian zakatilah sisanya.” (HR. Abu Ubaid, no. 918, Ibnu Abi Syaibah 3/194)
Dalam zakat barang dagangan, apa yang dikeluarkan?
Zakat dari barang dagangan harus dikeluarkan dalam bentuk uang tunai sesuai nilai barangnya, bukan dalam bentuk barang itu sendiri. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. (Lihat: Al-Kafi 1/301, Raudh At-Thalibin 2/273, Kasyaf Al-Qina’ 2/240)
Alasannya: Karena memberikan zakat dalam bentuk uang tunai lebih disukai oleh penerima zakat. Sebab, bisa jadi si miskin tidak butuh barangnya, lalu terpaksa menjualnya dengan harga murah. Atau, bisa juga barang tersebut tidak bisa dibagi sesuai bagian zakat yang seharusnya ia terima, atau tidak bisa dibagi rata ke beberapa orang miskin. Karena itu, cara yang lebih mudah, praktis, dan bermanfaat adalah dengan memberikan zakat dalam bentuk uang, bukan barang. (Lihat: Asy-Syarh Al-Mumti’ 6/141)
Barang dagangan dihitung dengan harga grosir atau eceran?
Pendapat pertengahan dalam masalah ini adalah:
• Untuk pedagang grosir, penilaian zakat dilakukan berdasarkan harga grosir.
• Sedangkan untuk pedagang eceran, dihitung dengan harga eceran.
(Lihat: Ahkam wa Fatawa Az-Zakah, hlm. 37)
Adapun jika seseorang berdagang dengan dua cara sekaligus (grosir dan eceran), maka penilaian dilakukan berdasarkan cara yang paling dominan dalam usahanya. (Lihat: Qadhaya Az-Zakah Al-Muashiroh: An-Nadwah Al-Ulaa, hlm. 433)
Bagaimana jika barang yang didagangkan adalah instrumen yang punya aturan zakat tersendiri, seperti berdagang hewan ternak?
Dalam madzhab Syafi’i dijelaskan: Bahwa jika barang dagangan itu adalah sesuatu yang sudah punya aturan zakat sendiri, seperti berdagang unta, maka tidak dikenakan dua jenis zakat sekaligus.
Artinya, kalau unta yang dimiliki untuk berdagang jumlahnya sudah mencapai nishab (misalnya minimal 5 ekor), maka zakatnya cukup ikut aturan zakat unta saja (yaitu 1 kambing), bukan zakat perdagangan berdasarkan nilai uangnya, apakah 5 unta itu sudah setara 85 gr emas atau belum.
Tapi kalau jumlah untanya belum sampai 5 ekor, dan memiliki nilai jual yang sudah mencapai nishab zakat uang, maka zakatnya dihitung berdasarkan nilainya. (Lihat: Al-Majmu’ 6/50)
Intinya:
• Kalau jumlahnya mencapai nishab zakat ternak → zakatnya mengikuti aturan zakat ternak.
• Kalau jumlah ternaknya belum sampai nishab zakat ternak, tapi nilainya mencapai nishab zakat uang → ikut aturan zakat perdagangan (dihitung berdasarkan uang).
Tujuannya supaya tidak terkena zakat dobel dan lebih adil untuk yang berdagang.
Bagaimana jika yang diperdagangkan adalah perhiasan emas dan perak, apakah yang dihitung beratnya, atau nilai jualnya?
Menurut mazhab Syafi’i, dalam hal emas dan perak yang dibentuk perhiasan, dan dimiliki untuk tujuan diperdagangkan, terdapat dua pendapat:
• Pendapat pertama: dikenakan zakat berdasarkan beratnya, untuk emas 85 gr, dan untuk perak 595 gr.
• Pendapatan kedua: dikenakan zakat berdasarkan nilainya, seperti zakat perdagangan (berdasarkan harga jualnya di pasar, meskipun secara berat belum mencapai nishab). (Lihat: Al-Majmu’ 6/53)
Namun, pendapat yang lebih kuat dan kami pilih adalah pendapat kedua, yaitu zakatnya dihitung berdasarkan nilai barang dagangannya, bukan berdasarkan berat emas atau peraknya. Sebab, hukum itu mengikuti alasan (’illat)-nya, dan dalam hal ini emas atau perak tersebut bukan sedang disimpan, tapi diperdagangkan. Karena tujuannya untuk diperjualbelikan, maka yang dihitung adalah nilai jualnya, bukan berat emas/perak-nya. Wallahu a’lam.
Tentang Saham
Apakah pemilik saham wajib membayar zakat?
Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa meninjau dari sisi regulasi perusahaan yang ingin melakukan penawaran saham perdana (IPO) di Indonesia.
Pertama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan bahwa perusahaan yang ingin IPO harus menjual minimal 150 juta lembar saham ke publik dengan harga minimal Rp100 per saham, serta memiliki minimal 500 pemegang saham.
Artinya, nilai saham yang ditawarkan ke publik saja sudah mencapai Rp15 miliar. Jika kita asumsikan sepertiga dari nilai ini digunakan untuk aset lancar (seperti modal kerja), maka nilainya sudah jauh melebihi nishab zakat. Apalagi jika dilihat dari total kekayaan perusahaan secara keseluruhan.
Kedua, syarat lain menyebutkan bahwa perusahaan harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan telah beroperasi minimal 12 bulan sebelum IPO. Ini berarti perusahaan tersebut setidaknya telah memiliki usia usaha selama satu haul (1 tahun).
(Sumber: https://flip.id/business/blog/syarat-ipo-perusahaan?)
Dari dua syarat ini, bisa disimpulkan bahwa perusahaan yang sudah melantai di bursa (Tbk) hampir pasti telah memenuhi syarat nishab dan haul dalam zakat. Maka, secara umum, saham yang dimiliki dalam perusahaan Tbk termasuk harta yang wajib dizakati.
Catatan:
Perusahaan Tbk (terbuka) dimiliki secara bersama oleh banyak orang. Meskipun dana dari para pemilik saham bercampur dalam perusahaan, maka menurut mayoritas ulama: zakat tetap dihitung secara pribadi oleh masing-masing pemegang saham, bukan sebagai satu kesatuan. (Lihat: Al-Mabsuth 3/195, Adz-Dzakhiroh 3/127, Al-Mughni 2/462)
Artinya, setiap pemilik saham harus menghitung sendiri apakah harta sahamnya sudah mencapai nishab dan telah dimiliki selama satu tahun (haul), untuk kemudian dizakati.
Dan untuk mengetahui berapa zakat yang harus dikeluarkan pemilik saham, kita harus mengetahui tujuan kepemilikannya, apakah untuk dagang atau investasi.
1. Saham yang Diperjualbelikan (Trading)
Jika saham dimiliki dengan tujuan untuk diperjualbelikan, maka saham tersebut termasuk dalam kategori barang dagangan. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan sebesar 2,5% dari total nilai sahamnya, berikut deviden yang diterimanya, dengan catatan nilai saham yang dimiliki mencapai nishab dan bertahan selama satu haul. (Lihat: Majmu’ Fatawa Ibni Baz 14/191, Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah: Al-Majmu’ah Al-Ulaa 9342)
2. Saham untuk Investasi Jangka Panjang
Cara menghitung zakat saham dengan tujuan investasi tidak bisa disamaratakan, karena sangat bergantung pada jenis perusahaannya:
A. Saham di Perusahaan Jasa
Jika Anda memiliki saham di perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan transportasi, hotel, periklanan, penerbangan, atau sejenisnya, maka yang wajib dizakati hanyalah hasil keuntungannya (dividen atau profit), bukan nilai saham itu sendiri.
Hal ini karena dana yang Anda tanamkan di perusahaan tersebut diwujudkan dalam bentuk aset tetap seperti gedung, kendaraan, kapal, pesawat, dan alat-alat lainnya. Ulama sepakat bahwa aset seperti ini tidak wajib dizakati jika tidak diperjualbelikan.
Dividen yang Anda terima dari saham seperti ini perlu diperhatikan: apakah jumlahnya sudah mencapai nishab atau belum.
Jika belum, Anda bisa menggabungkannya dengan uang lain yang Anda miliki.
Kalau sebelum menerima dividen Anda sudah punya uang yang mencapai nisab, maka dividen itu mengikuti hitungan haul uang yang sudah ada tadi.
Setelah genap satu tahun (haul), zakatnya dikeluarkan sebesar 2,5% dari total uang (termasuk dividen).
Contoh 1: Dividen Berdiri Sendiri
Anda menerima dividen sebesar Rp 160.000.000.
• Karena melebihi nisab (emas 85 gr sekitar Rp 145 juta), maka:
• Jika dividen ini disimpan selama 1 tahun (haul), maka wajib zakat.
• Hitungan zakatnya:
2,5% x Rp 160.000.000 = Rp 4.000.000
Contoh 2: Dividen Digabung dengan Uang Lain
Pak Umar menerima dividen Rp 60.000.000
Sebelumnya, ia sudah punya tabungan Rp 100.000.000 yang disimpan 8 bulan.
• Total uang setelah terima dividen:
Rp 160.000.000 → melebihi nisab
• Maka dividen ikut haul dari uang lama (tinggal tunggu 4 bulan lagi).
• Saat genap 1 tahun hijriah:
Zakat = 2,5% x Rp 160.000.000 = Rp 4.000.000
B. Saham di Perusahaan Industri atau Produksi
Jika perusahaan mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, seperti perusahaan pertambangan, pabrik tekstil, atau industri kimia, maka zakat dihitung dari nilai saham yang dimiliki dan dividen yang diterima, selama keduanya telah memenuhi syarat nisab dan haul. Namun sebelum dihitung zakatnya, nilai aset tetap yang tidak diperjualbelikan (seperti mesin, gedung, kendaraan produksi) harus dikurangkan dari total nilai saham.
Contoh:
Anda memiliki 400.000 lembar saham di salah satu PT industri, dengan harga per lembar Rp 2.500.
Maka nilai total saham Anda:
400.000 x 2.500 = Rp 1.000.000.000
Perusahaan tersebut memiliki aset tetap sebesar 40% dari total nilai, yang tidak diperjualbelikan. Maka zakat dihitung dari 60% nilai saham:
2,5% x Rp 600.000.000 = Rp 15.000.000
Tambahan:
Jika selama tahun tersebut Anda juga menerima dividen sebesar Rp 80.000.000, maka dividen itu ikut dihitung zakatnya (karena uang lama sudah memenuhi nishab dan haul).
2,5% x Rp 80.000.000 = Rp 2.000.000
Total zakat yang wajib Anda keluarkan:
Rp 15.000.000 (dari saham) + Rp 2.000.000 (dari dividen) = Rp 17.000.000
(Lihat: Asy-Syamil fii Zakatil Ashum, hlm. 93, Zakatul Ashum was Sanadat wal Wariq An-Naqdiy, hlm. 16-18, dengan penyesuaian dan penyederhanaan)
Catatan:
Zakat tidak diwajibkan dua kali atas satu harta. Jika perusahaan tempat saham dimiliki telah menunaikan kewajiban zakat atas kekayaan perusahaannya, maka pemilik saham tidak perlu mengeluarkan zakat lagi untuk saham yang sama. Namun, apabila perusahaan tidak menunaikan zakat, maka pemilik saham berkewajiban mengeluarkan zakatnya secara pribadi. (Lihat: Asy-Syarh Al-Mumti 6/148)
Selain itu, penting bagi setiap calon investor untuk bersikap selektif dalam memilih saham. Tidak semua saham yang diperjualbelikan di pasar modal bersifat halal. Jika suatu perusahaan bergerak di bidang yang diharamkan dalam Islam, seperti industri rokok, minuman keras, atau perbankan berbasis riba, maka haram hukumnya memiliki saham di perusahaan tersebut. Sebab, kepemilikan saham berarti ikut serta dalam aktivitas dan keuntungan perusahaan.
Karena itu, sebelum membeli saham, pastikan bahwa bisnis utama perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Wallahu a’lam.